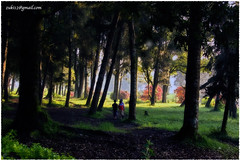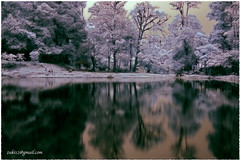Kita Tak Akan (Pernah) MerdekaRadhar Panca Dahana - Kompas
Kita Tak Akan (Pernah) MerdekaRadhar Panca Dahana - KompasDalam sebuah dialog interaktif di satu stasiun televisi swasta, seorang penanya mempertanyakan makna kemerdekaan, ketika rakyat di pinggir-pinggir terluar negeri ini sama sekali tidak merasakan perbedaan hidup, bahkan sejak ratusan tahun nenek moyang mereka hidup di pulau-pulau kecil itu. Terbelakang, tak tersentuh, tak terperhatikan, bahkan kian terimpit desakan hidup yang terus mendera.
Berbagai ekspresi lain, di berbagai media, hampir semua juga mempertanyakan apakah sebenarnya kita telah merdeka. Ketika tiga hal pokok dalam hidup kita (baca: ekonomi, kesehatan, dan pendidikan) kian hari justru menjadi tekanan, menjadi beban yang memberat, apakah teriakan "merdeka!" masih punya getaran? Ketika untuk beraktualisasi, bekerja, mengatur diri dan masyarakat, berpolitik, menciptakan pelbagai sistem, bahkan untuk mulai berpikir saja kita sudah dependen atau malah—dengan sengaja—mengikatkan diri pada standar-standar yang tidak kita miliki sendiri, apakah kita memang sudah merdeka?
Maka, ketika teriakan-teriakan "merdeka!" itu terserukan di banyak mimbar, pawai-pawai berderak, bendera dikibarkan, panggung dibuka, dan segala kemeriahan dilakukan dalam peringatan kemerdekaan, sesungguhnya dalam waktu yang bersamaan kita bingung—bahkan tak tahu—apa makna kemerdekaan itu.
Bagi kita saat ini, kemerdekaan tidak lagi milik ayah, ibu, kakek atau moyang kita di masa 50, 60, atau 70 tahun lalu, dalam arti dan signifikansi. Ia bergeser dan berubah, bahkan radikal, mengikuti revolusi peradaban dunia yang mengisi dan mengiringinya. Dan, dalam kebingungan itu, kita—satu per satu—mengkreasi makna dan menarik signifikansi kemerdekaan menurut versi kita sendiri.
Kata ajaib itu kini menjadi personal, subyektif. Tidak lagi komunal-obyektif. Seperti juga terbaca pada komentar puluhan orang yang dikutip Kompas dalam edisi kemerdekaannya lalu. "Merdeka" artinya aku bisa mengembangkan diri dalam keterbatasan, berbuat banyak untuk orang lain, memulung sampah yang berserak di sembarang tempat, atau… berteriak keras di stadion sepak bola!
Justru berlawanan dengan semangat globalisasi, universalitas makna kemerdekaan kini luntur, laiknya warna sepuhan. Saat orang-orang dengan tinju yang keras melantangkan kebebasan, demokrasi, dan egaliterianisme, yang terjadi adalah semua mulut memiliki lekuk lidahnya sendiri, kebenaran subyektifnya sendiri. Maka, makna yang dahulu menyatukan 60 juta penduduk republik ini, seperti pecah, terburai menjadi rumah-rumah makna yang kecil, dan sepi….
Siapa telah merdeka?Dalam bumi yang kian datar ini, dalam adab yang khaotik dan teknologi yang segala mengalami dependensi ini, siapa sebenarnya yang telah merasakan sungguh-sungguh merdeka? Adakah bangsa di atas planet ini yang dapat menegakkan diri dan kemauannya sendiri tanpa tekanan dan desakan hebat dari luar maupun dalam?
Adakah bangsa China merdeka, ketika ia harus membuka diri pada pasar dunia, dan harus kehilangan 10.000 pabrik hanya karena mainan plastik? Adakah bangsa Iran merdeka, dalam tekanan Amerika Serikat (AS), Eropa, dan organisasi dunia?
Adakah AS sendiri merdeka ketika industri terbesarnya, senjata, terancam ambruk pasca-perang dingin, atau saat ia terjebak (baca: menjebak dirinya sendiri) dalam ilusi terorisme yang justru ia kreasi sendiri? Adakah Indonesia merdeka, waktu kita meneriakkan "demokrasi" tapi kita tak memiliki ide apa pun mengenai itu, lalu dengan membabi buta mengopi sistem orang lain ke sana-sini?
Betapa menggelikan, saat menteri paling bertanggung jawab dalam soal ekonomi negeri ini membela diri dengan canggung soal pasar bebas, liberalisasi, dan kurs. Lalu, seorang profesor pemenang Nobel dengan santainya menunjukkan betapa argumentasi menteri yang dibanggakan itu cuma menunjukkan betapa tidak merdekanya pemerintahan republik ini. Ketika bursa dan kurs anjlok berat, para menteri yang bertanggung jawab, bahkan otoritas moneter hanya bisa menukas, "Kita berharap tren ini tidak berlangsung lama."
Berharap? Ya, kita hanya bisa berharap: apa dan siapa yang menjadi gantungan hidup bangsa ini, yang ternyata kekuatan luar, tidak berbuat sesuatu yang lebih buruk. Tepatnya: mengasihani kita. Bangsa dan negeri impian, surga dunia yang kini laun dan santun mengubah dirinya seperti neraka.
Secara individual, siapakah dari kita yang telah merdeka? Untuk ukuran negeri yang dalam hikayatnya ramah dan jujur ini, mungkin hanya koruptor yang merdeka. Merdeka mengorupsi di mana dan kapan saja karena sejawat kanan-kiri merestui (agar mereka juga dapat melakukan hal yang sama).
Mereka merdeka, untuk jadi tokoh, selebritas, pahlawan, pejabat, ulama, apa saja mereka mau. Bahkan, setelah jadi napi, masih lenggang menjabat kembali. Mungkin hanya negeri ini, yang dengan santai mempermisikan napi terpenjara memimpin organisasi nasional yang penting.
Bisa kita merdeka?Selebihnya, bangsa ini hingga ke tingkat pribadi, adalah makhluk-makhluk Tuhan yang tetap unggul tapi terpenjara. Bukan hanya oleh penyakit, kemiskinan dan kebodohan belaka, tetapi juga pada tingkat intelektual, spiritual bahkan fisikal.
Secara spiritual dan intelektual kita mafhum dengan cepat. Di tingkat fisikal, phisycal performance, aha… kitalah konsumen terbaik, tersetia, dan terboros untuk kebutuhan-kebutuhan yang direkayasa berbagai pabrikan dunia melalui gerai-gerai di plaza, mal, square, hypermarket, majalah, koran, televisi, hingga kelontong di desa dan pinggiran kota. Dari produk kesehatan, kecantikan, hingga aksesori di pinggang kita.
Lalu, apakah sesungguhnya kemerdekaan itu? Sungguhkah kita mengenal kemerdekaan itu? Atau, apa kemerdekaan itu benar-benar perlu? Lebih ringannya, mungkinkah kemerdekaan itu terwujud? Jujur saja, pertanyaan-pertanyaan ini terasa pesimistis. Tapi tampaknya ia lebih realistis ketimbang romantisme semacam "semangat 45" atau "right or wrong is my country".
Yang pertama, universalisme kemerdekaan kini sudah ada di recycle bin. Semua pihak dapat mengambil signifikansinya sendiri-sendiri. Dan itu sah.
Kedua, kemerdekaan itu jangan-jangan ilusif atau sejenis idealisasi: bayangan kesempurnaan, semacam masyarakat komunis atau nirwana di dunia. Barangkali ia perlu, ia ada, tetapi secara fakultatif, dalam arti ia ada dan bermakna pada kondisi-kondisi tertentu (waktu, tempat, dan situasi). Selebihnya, kita mau tak mau—ini sungguh taken for granted—harus tidak merdeka.
Bukankah kita mulai tidak merdeka justru di puncak kebahagiaan mahligai perkawinan? Bukankah tidak merdeka, saat Anda masuk dalam dunia kerja? Apakah saudara merdeka bertetangga di satu perumahan, kluster, apartemen, atau kampung di pinggiran? Bahkan, sungguhkah kita merdeka saat napas dan teriakan pertama kita lakukan di usia terdini kita?
Ketidakmerdekaan tampaknya adalah bagian hidup kita yang terpisahkan. Termasuk di dalamnya keterbatasan kita sebagai manusia, sebagai pribadi. Dan, kita, ternyata bisa hidup secara relatif baik selama ini bersamanya. Juga sebagai bangsa, sebagai negara dan satu pemerintahan, tak satu pun luput dari ketidakmerdekaan. Persoalannya, tinggal bagaimana kita menyikapinya.
Buat saya, ketidakmerdekaan tidak perlu jadi ancaman, tapi tantangan. Ia justru untuk mengoptimasi kemanusiaan kita.
Sebagaimana ukuran kualitas hidup lainnya, kemerdekaan—juga ketidakmerdekaan—ada tingkatan, level, atau maqam-nya. Dan, setiap waktu berlalu, yang kita upayakan adalah meraih level atau maqam yang lebih tinggi.
Hanya orang bodoh dan tidak menghargai diri—juga kemanusiaannya—sendiri yang justru getol meningkatkan level ketidakmerdekaannya. Koruptor, contohnya. Tentu saja mudah-mudahan bukan Anda salah satunya, kan?